PADA mulanya adalah emas. Tanah di Pulau Sumatra mengandung logam mulia itu. Masyarakat di pulau ini, mulai dari ujung Utara sampai Selatan, hidup sebagai penambang emas. Mereka melakukannya dengan sangat mudah, hanya mengayak tanah yang ada secara tradisional, menggunakan tenaga manusia.
Thomas Diaz, seorang pejabat Belanda yang bertanggungjawab menjalankan program Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) di wilayah Selat Malaka, melakukan ekspedisi ke dalam kawasan masyarakat Minangkabau pada tahun 1684, dia menemukan masyarakat menjadikan emas sebagai mata pencaharian utama. Mereka mengambil emas di sungai-sungai begitu mudah, sehingga pemimpin kerajaan terpaksa harus membatasi pekerjaan mendulang emas dan masyarakat diharuskan bekerja sebagai petani.
Catatan perjalanan Thomas Diaz juga merekam bagaimana dia melakukan diplomasi perdagangan dengan raja-raja penguasa Selat Malaka agar VOC diberi izin untuk berdagang. Saat itu, berbekal surat pengantar yang ditandai adanya cap kerajaan, Diaz bisa berhubungan langsung dengan para saudagar emas yang sudah lebih dahulu mendapat izin dari kerajaan. Saudagar-saudagar emas itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari pedagang Gujarat, China, Persia, India, Arab, sampai Melayu, bekerja mengumpulkan emas dari masyarakat penambang dan menjualnya kepada pihak yang bersedia membeli dengan harga lebih tinggi.
Jauh sebelum VOC datang, pamor Pulau Sumatra sebagai tanah emas santer ke seluruh dunia. Tanah ini disebut swavarnadvipa yang artinya tanah emas. Literatur-literatur lama mengisahkan, orang-orang dari berbagai belahan dunia datang untuk mengambilnya. Bahkan, sebagaimana dikisahkan dalam Kitab Perjanjian Lama (Alkitab-Surat Raja-Raja Pertama 9:26-8 10: 10-3), Raja Salomo (Sulaiman) mengirimkan ekspedisi berupa pasukan kapal-kapal besar ke Ophir yang dipimpin Raja Hiram untuk mengambil emas. Ternyata, bukan hanya emas yang didapat, tetapi juga batu-batu mulia dan kayu cendana. Sukses ekspedisi itu membuat Raja Salomo kembali mengirim ekspedisi ke Ophir pada tahun 945 SM, dan pulang kembali membawa emas.
Emas di Sumatra juga terekam dalam sastra India. Daerah ini disebut Swarnadwipa (tanah emas), sebuah daerah yang harus didatangi karena emas adalah logam yang mampu mengangkat derajat manusia. Para penambang pun ikut serta, berjejah di kapal-kapal layar yang kadang kehilangan peta navigasi, lalu mendarat di Pulau Jawa dan akhirnya menjadi petani.
Yang mendarat di Malaka, kemudian masuk lewat muara sungai-sungai besar, sebagian masuk ke Binanga (kata ini berasal dari bahasa Sansekerta dari kata asli “minanga”). Sebagian lainnya sampai di Padang Panjang, lalu dari sana mereka migrasi menelusuri sumber emas, dan kemudian tiba di pesisir Barat Pulau Sumatra, di daerah yang kemudian dikenal sebagai pesisir pantai Natal. Kelak, para penambang emas yang sampai ke Natal, diikuti oleh para mubalik yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Lingga Bayu.
Kerajaan Lingga Bayu adalah sebuah kerajaan yang banyak menghasilkan emas, terutama pada awal abad ke-18. Kerajaan itu mulai berkurang pamornya setelah pesona emas yang didulang di sungai-sungai kecil mulai dibatasi. Pemerintah mendorong rakyat untuk menjadi petani, sementara emas tidak boleh didulang setiap saat. Kebijakan itu membuat pamor Kerajaan Lingga Bayu berkurang dan akhirnya kerajaan itu kini hanya nama sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, tepatnya di Lanskap Pesisir Pantai Natal.
Sebagai daerah tambang emas kuno, sampai hari ini masyarakat di Lingga Bayu masih menanbang. Cuma, mereka menambang dengan teknik yang berbeda, menciptakan lubang-lubang galian yang dalam pada tanah. Beberapa kali lubang itu runtuh dan menimbun penambang. Seperti kejadian 28 April 2022 lalu, belasan orang tertimbun galian lubang tambang dan tewas.
Mereka, penambang yang tewas itu, hanya pekerja (buruh) dari para toke pemilik lubang tambang. Lubang-lubang tambang itu dikuasai para pemodal yang ternyata banyak di antara mereka adalah elite pemerintah. Beberapa elite pemerintah di Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal disebut-sebut sebagai pemilik lubang tambang. Mereka mendapat hak setelah berinvestasi senilai Rp 15 juta sampai Rp 100 juta per lubang tambang. Mereka didatangi oleh orang-orang, menawarkan lubang-lubang tambang itu, dan sebagian mengaku beruntung berinvestasi.
Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab atas matinya para penambang di lubang-lubang tambang itu? “Mikir!” kata Cak Lontong. ***

BUDI P. HATEES
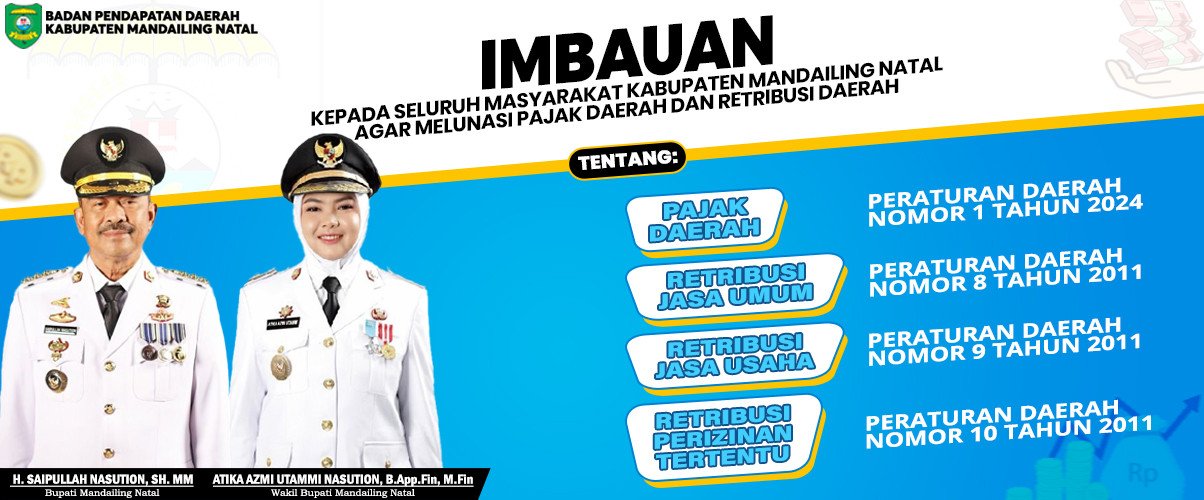





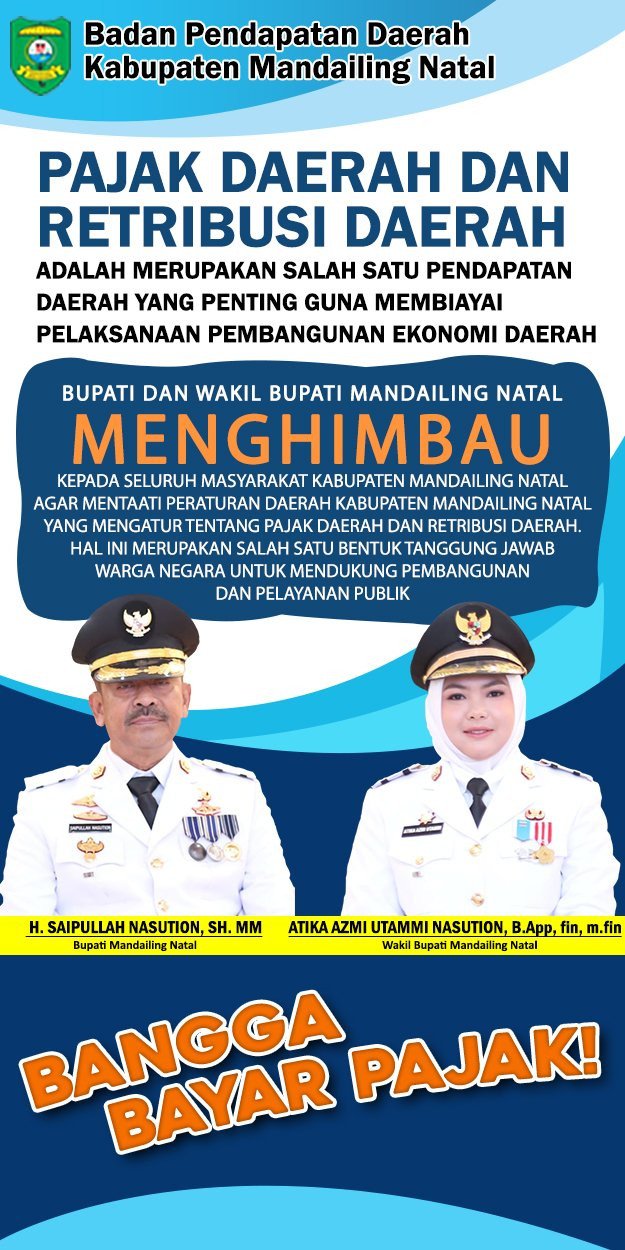




Discussion about this post