PESANTREN, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah memainkan peran penting dalam membentuk wajah sosial bangsa. Dalam berbagai kajian historis, pesantren dipandang bukan sekadar institusi pendidikan, tetapi pusat peradaban, benteng moral, dan ruang transformasi sosial. Di tengah derasnya modernisasi dan dominasi pendidikan Barat yang menitikberatkan pada aspek kognitif, pesantren tetap bertahan dengan model pendidikan berbasis akhlak, adab, dan karakter. Stereotip yang dialamatkan kepada pesantren, seperti dianggap kolot dan tertutup, sejatinya lahir dari miskonsepsi terhadap hakikat pendidikan pesantren yang justru mengutamakan humanisme spiritual.
Sejarah membuktikan bahwa pesantren tidak hanya mendidik santri menjadi ahli agama, tetapi juga melahirkan pemimpin sosial, pejuang bangsa, dan penggerak kebudayaan. Tokoh seperti KH. Hasyim Asy’ari, KH. Ahmad Dahlan, hingga KH. Saifuddin Zuhri adalah bukti nyata kontribusi pesantren dalam sejarah kebangsaan. Pesantren telah mengajarkan bahwa ilmu tidak hanya untuk dikuasai, tetapi juga diamalkan demi kemaslahatan masyarakat. Dalam pandangan mereka, pendidikan sejati adalah yang mencerahkan akal dan membersihkan hati.
Berbeda dengan pendidikan Barat yang lebih menitikberatkan pada kemampuan intelektual dan penguasaan rasionalitas, pesantren menawarkan pendidikan yang memadukan kognisi, afeksi, dan spiritualitas. Model pendidikan Barat sering kali dianggap kering dari nilai moral, sebab mengejar objektivitas ilmu tanpa mempertimbangkan dimensi etika. Immanuel Kant pernah berbicara tentang rasionalitas murni, namun pesantren justru mengajarkan bahwa akal yang tidak dibimbing oleh hati hanya akan melahirkan kesombongan intelektual.
Inovasi Sosial
Salah satu stereotip yang sering diarahkan kepada pesantren adalah anggapan bahwa sistemnya tradisional dan tidak relevan dengan zaman. Namun faktanya, pesantren kini menjadi pusat inovasi sosial. Banyak pesantren membuka program kewirausahaan, teknologi, jurnalistik, hingga advokasi sosial. Hal ini membuktikan bahwa pesantren bukan lembaga statis, tetapi dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan prinsip spiritualnya.
Saifuddin Zuhri, dalam refleksi pendidikannya, menggambarkan pesantren sebagai ‘kawah candradimuka’ yang menempa santri menjadi manusia pengabdi, bukan sekadar pemikir. Ia menegaskan bahwa pesantren adalah ruang pembentukan karakter bangsa, tempat lahirnya manusia mandiri yang berani melawan penindasan dan memperjuangkan keadilan. Menurutnya, kekuatan pesantren bukan pada bangunan fisik, melainkan ruh perjuangan yang hidup di dalamnya.
Dalam perspektif transformasi sosial, pesantren telah menjadi agen perubahan di masyarakat. Pesantren mengajarkan konsep kesederhanaan, kerja kolektif, dan kepedulian sosial. Santri tidak hanya belajar membaca kitab, tetapi juga belajar mengolah tanah, memimpin masyarakat, dan menyelesaikan konflik. Hal ini menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan, bukan sekadar pusat pengajaran.
Fenomena lulusan pesantren yang kini terjun ke berbagai sektor publik menjadi bukti relevansi pendidikan pesantren. Mereka hadir sebagai pendidik, aktivis sosial, budayawan, bahkan politisi. Dalam dunia politik, lulusan pesantren dikenal sebagai sosok yang merakyat, santun, dan berprinsip. Mereka terlatih dalam berdialog, memiliki wawasan kebangsaan, dan mampu menjaga harmoni masyarakat majemuk.
Dalam bidang pendidikan, lulusan pesantren membawa pendekatan humanis dan spiritual. Mereka memahami bahwa mendidik bukan sekadar mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi menuntun jiwa. Di ruang kelas, mereka menghidupkan tradisi diskusi, musyawarah, dan keteladanan, sebagaimana mereka belajar di pesantren melalui sorogan, bandongan, dan pengabdian.
Dari sisi budaya, pesantren menjadi penjaga warisan tradisi Nusantara. Pesantren tidak menolak budaya lokal, melainkan mengislamkannya dengan nilai tauhid. Tradisi seperti shalawat, hadrah, barzanji, hingga tahlilan menjadi ruang spiritual yang membangun kolektivitas masyarakat. Pesantren hadir sebagai jembatan antara agama dan budaya, bukan tembok yang memisahkan keduanya.
Dalam konteks sosial, pesantren menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat kecil. Di berbagai desa, pesantren membuka klinik kesehatan, dapur umum, hingga majelis taklim. Pesantren mengajarkan santri untuk hidup bersama rakyat, bukan menjauh dari mereka. Ini berbeda dengan sebagian lembaga pendidikan elit yang menciptakan jarak sosial antara intelektual dan masyarakat.
Pesantren juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab moral. Santri tidak hanya diuji melalui ujian tulis, tetapi diuji melalui laku hidup. Mereka diajarkan untuk bangun sebelum fajar, membersihkan lingkungan, dan berkhidmah kepada kyai. Inilah pendidikan karakter sejati yang tidak ditemui dalam sistem pendidikan modern yang hanya berbasis penilaian angka.
Ketika dunia pendidikan nasional menghadapi krisis moral, dari perundungan, tawuran, hingga penyimpangan sosial, pesantren menawarkan jalan pulang. Pendidikan yang tidak menanamkan akhlak hanya akan mencetak generasi cerdas namun kehilangan arah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qalam:4, ‘Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti agung.’ Ayat ini menjadi dasar bahwa pendidikan sejati berpuncak pada akhlak.
Hadis Nabi pun menegaskan, ‘Innīmā bu‘itstu li utammima makārimal akhlāq’ (Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia). Pesantren memegang teguh misi ini. Mereka memahami bahwa akhlak bukan pelengkap, tetapi inti dari segala ilmu. Tanpa akhlak, ilmu menjadi kekuatan yang membahayakan.
Solidaritas Sosial
Kiai, sebagai kendali sebuah pesantren memiliki peran besar dalam membentuk konstruk sosial masyarakat. Sayfa Auliya Achidsti dalam bukunya “Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial” (2015) mengatakan bahwa dalam banyak kasus, kiai sering berperan kreatif dalam perubahan sosial. Masalah yang dihadapinya adalah bagaimana kebutuhan akan perubahan itu dapat dipenuhi tanpa merusak ikatan-ikatan sosial yang telah ada sebelumnya, melainkan justru memanfaatkan ikatan-ikatan itu sebagai mekanisme perubahan sosial yang diinginkannya.
Untuk itulah kyai menjadikan pesantren sebagai ekosistem pendidikan berbasis komunitas. Santri belajar hidup bersama, saling membantu, dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Ini berbeda dengan model kompetitif dalam pendidikan modern yang sering menumbuhkan egoisme. Pesantren membangun solidaritas sosial yang kuat, modal utama dalam membangun bangsa.
Dalam era globalisasi, tantangan terbesar pendidikan adalah menjaga identitas. Pesantren hadir sebagai benteng moral bangsa. Mereka mengajarkan keterbukaan tanpa kehilangan jati diri. Pesantren melahirkan generasi yang mampu berdialog dengan zaman tanpa tenggelam dalam arusnya. Inilah yang dibutuhkan Indonesia hari ini.
Pesantren bukan sekadar warisan masa lalu, melainkan harapan masa depan. Di saat pendidikan nasional mencari arah, pesantren menawarkan keseimbangan antara ilmu dan iman, akal dan hati, individu dan masyarakat. Pesantren membuktikan bahwa transformasi sosial tidak hanya lahir dari revolusi teknologi, tetapi dari revolusi akhlak.
Sudah saatnya negara melihat pesantren bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai model pendidikan alternatif. Pesantren telah menunjukkan bahwa membangun bangsa tidak cukup dengan kecerdasan, tetapi harus dengan kebijaksanaan. Di tengah krisis moral, pesantren adalah lentera yang tak pernah padam, menuntun jalan peradaban Indonesia yang beradab. (*)
Penulis: Sunhaji | Guru Besar bidang Ilmu Pengelolaan dan Pembelajaran sekaligus Wakil Rektor 3 UIN Saizu Purwokerto.
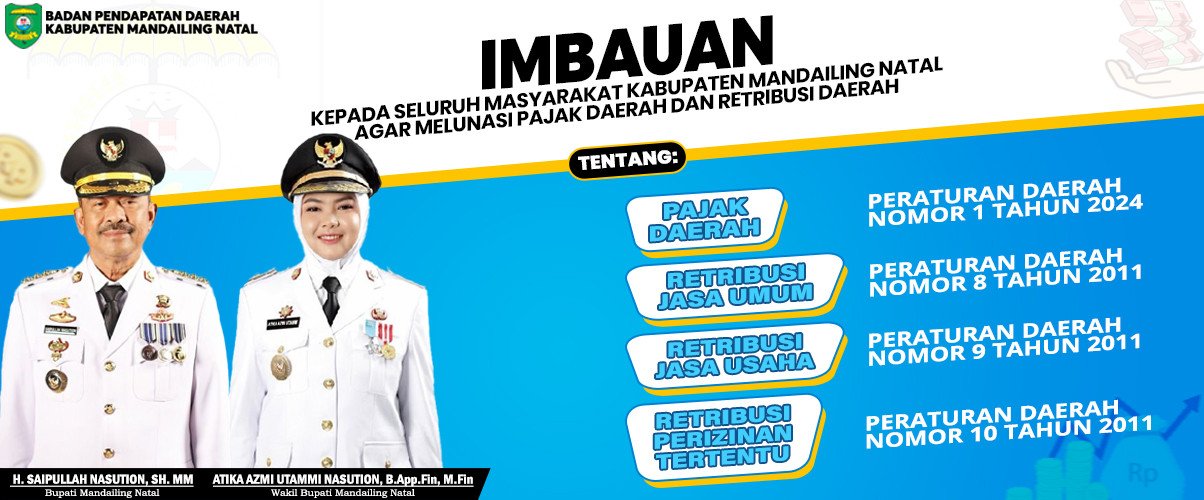





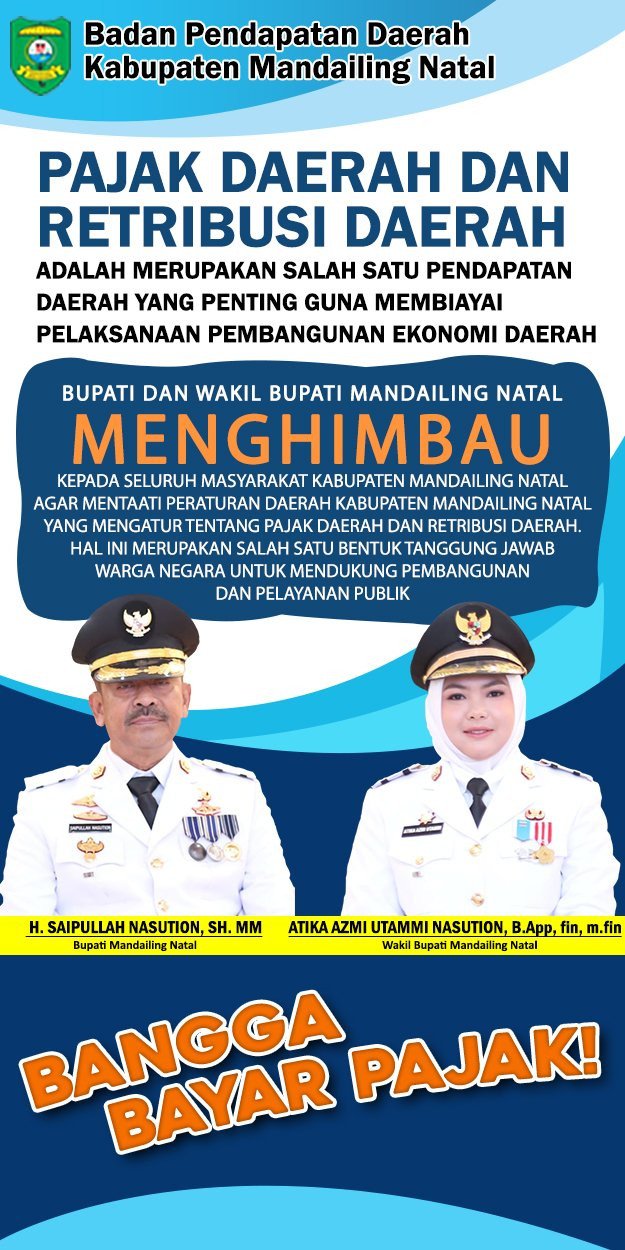




Discussion about this post